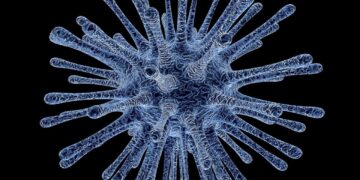Kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang sedang mengantar pesanan makanan, menjadi simbol paling telanjang dari rusaknya relasi negara dengan rakyatnya. Ia bukan aktivis garis depan, bukan pula mahasiswa yang sedang berorasi, melainkan seorang pekerja kecil yang berusaha mengais rezeki di tengah hiruk-pikuk demonstrasi di sekitar Gedung DPR.
Namun justru nyawanya melayang, dilindas kendaraan taktis aparat yang seharusnya melindungi. Tragedi ini memicu gelombang kemarahan yang tak terbendung, dari Jakarta ke Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Seakan-akan seluruh Indonesia menemukan satu wajah: wajah ketidakadilan yang terwakili dalam diri Afan.
Kasus ini menjalar luas karena publik melihatnya bukan sekadar kecelakaan, melainkan potret negara yang gagal memberi jaminan paling dasar: rasa aman bagi warganya.
Bagi masyarakat, Affan adalah cermin. Jika seorang rakyat kecil yang hanya mencari nafkah bisa dilindas begitu saja, lalu siapa lagi yang bisa merasa aman? Pertanyaan itu lebih mengerikan daripada dentuman gas air mata.
Pemerintah, terutama kepolisian, tampak gagap menghadapi kemarahan publik. Permintaan maaf Kapolri dan janji investigasi tentu perlu, tetapi terasa terlambat. Masyarakat sudah terlanjur percaya bahwa pola represif aparat bukanlah insiden sekali ini, melainkan kebiasaan yang diwariskan.
Dari tragedi 1998, 2019, 2020, hingga kini 2025, pola yang sama berulang: aparat tak bisa membedakan antara menjaga ketertiban dan menebar teror. Presiden boleh saja menyatakan duka dan menjanjikan rumah bagi keluarga korban, namun janji material tidak akan menghapus luka kolektif. Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural kepolisian—pengendalian massa yang humanis, akuntabilitas yang nyata, dan keberanian menindak aparat yang menyeleweng, bukan sekadar mengorbankan “oknum” setiap kali ada tragedi. Jika hal ini gagal dilakukan, pemerintah akan terus berhadapan dengan gelombang protes yang tak pernah benar-benar padam.
DPR pun tidak bisa cuci tangan. Demonstrasi awal lahir dari penolakan publik terhadap kenaikan tunjangan DPR di tengah situasi ekonomi yang menjerat rakyat. Bagi masyarakat, DPR sudah lama menjadi simbol kemewahan yang timpang: kerja minim, fasilitas maksimal. Maka ketika darah rakyat kecil tumpah di sekitar gedung megah Senayan, kemarahan pun berubah menjadi legitimasi moral untuk mengepung lembaga yang seharusnya mewakili mereka.
Namun rakyat pun tak sepenuhnya suci. Kemarahan yang wajar sering kali dibajak oleh aksi-aksi destruktif yang justru memperburuk keadaan. Perusakan kantor polisi, pembakaran fasilitas publik, atau penyerangan terhadap aparat tidak menyelesaikan masalah, malah memperkeruhnya. Energi kolektif yang lahir dari tragedi Affan seharusnya diarahkan menjadi tekanan politik yang terukur, bukan amarah liar yang memakan korban baru.
Tak kalah berbahaya adalah kehadiran pihak-pihak yang sengaja mendompleng momentum. Oknum provokator, entah dari kelompok politik, kepentingan ekonomi, atau bahkan penyusup yang mencari kerusuhan, memperkeruh situasi. Mereka menyalakan api lebih besar demi agenda sempit, sementara rakyat biasa yang jadi tameng di jalanan. Mereka inilah wajah paling busuk dari setiap demonstrasi: menunggangi duka dan kemarahan untuk kepentingan yang tidak pernah jujur.
Tragedi Affan Kurniawan adalah titik balik: negara ditelanjangi oleh ketidakmampuannya, rakyat tersadar akan rapuhnya posisi mereka, dan oknum provokatif terbongkar kelicikannya. Namun yang paling berbahaya adalah krisis kepercayaan yang semakin dalam.
Rakyat kehilangan sabar, aparat kehilangan legitimasi, dan DPR kehilangan wibawa. Jika pemerintah hanya menambal dengan permintaan maaf tanpa reformasi, luka ini akan terus bernanah. Jika rakyat hanya melampiaskan dengan amarah tanpa arah, energi perubahan akan sia-sia. Dan jika provokator terus menunggangi, negeri ini akan terus terseret dalam lingkaran konflik.
Tragedi Affan seharusnya menjadi alarm: bahwa demokrasi tidak bisa terus dijalankan dengan cara membungkam suara dan menindas tubuh rakyat. Sebab sekali rakyat kehilangan rasa percaya, negara bisa kehilangan segalanya.