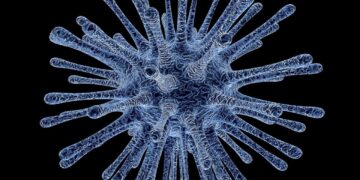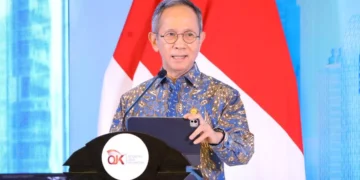Kasus bullying di sekolah kembali menyita perhatian publik. Setiap kali peristiwa seperti ini mencuat, masyarakat tak hanya menyoroti pelaku, tetapi juga bagaimana sekolah menyelesaikannya. Belakangan, istilah restorative justice kerap digunakan sebagai pendekatan penyelesaian. Pelaku diminta meminta maaf, korban diminta memaafkan, dan kasus pun dianggap selesai.
Namun pertanyaannya: apakah “damai” berarti adil ketika korban masih terluka?
“Keadilan yang tergesa bisa berubah menjadi pembiaran,” ujar psikolog anak Seto Mulyadi, menegaskan bahwa pemulihan psikologis korban tidak boleh dikorbankan demi citra lembaga pendidikan.
Restorative Justice: Antara Idealisme dan Realita
Secara konsep, restorative justice adalah pendekatan penyelesaian masalah yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Fokusnya bukan pada hukuman, tetapi pada tanggung jawab pelaku dan pemulihan korban. Konsep ini diadaptasi dari sistem hukum pidana dan kini banyak diterapkan di lingkungan pendidikan.
Di atas kertas, pendekatan ini tampak ideal: mendidik pelaku untuk bertanggung jawab tanpa menghancurkan masa depannya. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah keliru memahami makna “pemulihan”.
“Banyak sekolah masih salah kaprah. Mereka menganggap restorative justice adalah cara cepat menutup kasus, padahal tanpa pendampingan psikolog, itu hanya bentuk lain dari pembiaran,” kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji (Kompas.com, 2023).
Beberapa kasus menunjukkan, setelah proses damai, korban justru harus pindah sekolah karena tidak sanggup berinteraksi kembali dengan pelaku. Sementara pelaku tetap diterima di lingkungan yang sama, bahkan kembali beraktivitas tanpa konsekuensi nyata.
Ketika korban harus pergi dan pelaku tetap tinggal, keadilan kehilangan maknanya.
Celah Keadilan yang Masih Menganga
Setidaknya ada empat celah yang kerap muncul dalam penerapan restorative justice di sekolah:
- Korban belum benar-benar pulih. Permintaan maaf tidak menyembuhkan trauma.
- Kesenjangan kekuasaan. Korban sering ditekan agar menerima “damai” demi nama baik sekolah.
- Minimnya pemantauan. Setelah surat perdamaian ditandatangani, sekolah menganggap kasus selesai.
- Penyalahgunaan konsep RJ. Kadang dijadikan tameng administratif untuk menjaga citra lembaga.
Pakar hukum pidana Eva Achjani Zulfa (UI) mengingatkan dalam forum publik (2022): “Restorative justice bukan berarti meniadakan tanggung jawab pelaku, melainkan menyeimbangkan hak korban dan kewajiban pelaku secara manusiawi.”
Sayangnya, keseimbangan itu sering hilang ketika lembaga pendidikan lebih fokus pada “selesainya kasus” ketimbang pemulihan korban.
Antara Keadilan dan Pelanggaran HAM
Dalam konteks hukum nasional, praktik yang tergesa-gesa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti, menegaskan dalam rilis resmi (2023): “Sekolah tidak boleh mengorbankan hak korban hanya demi menjaga citra lembaga. Anak korban bullying harus mendapatkan perlindungan dan layanan psikologis hingga benar-benar pulih.”
Jika korban masih takut datang ke sekolah, masih menangis setiap kali diingatkan pada kejadian itu, maka tidak ada keadilan yang tercapai.
Dalam kondisi seperti ini, perdamaian yang dipaksakan justru melanggar hak korban atas rasa aman — dan itu bentuk pelanggaran HAM yang paling halus tapi nyata.
Hak korban untuk merasa aman adalah bagian dari hak asasi manusia — bukan sekadar urusan internal sekolah.
Mewujudkan Restorative Justice yang Berimbang
Restorative justice tetap bisa menjadi pendekatan yang bijak, asal dijalankan dengan empati dan keseimbangan.
Beberapa langkah yang bisa diterapkan sekolah antara lain:
1. Pendampingan psikolog profesional bagi korban dan pelaku.
2. Mediator independen agar proses tidak bias kepentingan lembaga.
3. Pemantauan pasca-kasus untuk memastikan perubahan perilaku pelaku.
4. Ruang aman bagi korban — termasuk opsi pindah kelas atau konseling rutin.
5. Pelibatan lembaga eksternal seperti KPAI, Komnas HAM, atau Dinas Pendidikan.
Restorative justice sejati bukan tentang menutup kasus, tetapi membuka ruang pemulihan bagi semua pihak.
Restorative justice adalah langkah maju dalam dunia pendidikan. Tetapi tanpa keseimbangan, pendekatan ini bisa berubah menjadi jebakan moral — di mana korban diam karena terpaksa, dan pelaku merasa cukup dengan sekadar maaf.
“Sekolah harus menjadi ruang aman, bukan ruang trauma,” tulis aktivis pendidikan Najeela Shihab dalam refleksinya di Narasi Institute (2023).
Keadilan sejati bukan tentang menenangkan publik, melainkan menyembuhkan manusia.
Dan di dunia pendidikan, pemulihan baru benar-benar terjadi ketika korban merasa aman, pelaku belajar bertanggung jawab, dan sekolah berani berpihak pada kemanusiaan.