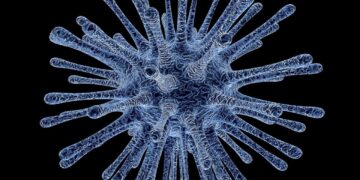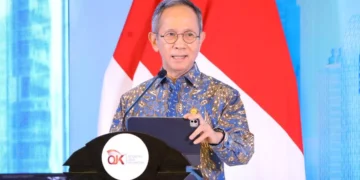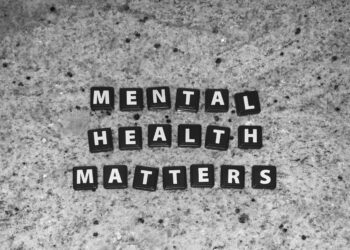Setiap akhir pekan, pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar ramai dipadati pengunjung. Tidak semua datang untuk belanja. Sebagian besar hanya melihat-lihat, mencoba barang, berpose di depan etalase, dan bertanya-tanya kepada penjaga toko tanpa pernah membeli. Mereka dikenal dengan julukan yang menggelitik: Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya). Fenomena ini bukan sekadar perilaku kasual masyarakat urban, tetapi gejala sosial yang menarik untuk ditelaah dari sudut pandang psikologi ekonomi.
Tindakan Rojali dan Rohana mencerminkan ketegangan antara keinginan konsumsi yang dibentuk oleh lingkungan kapitalistik dengan kapasitas ekonomi riil yang terbatas. Mall bukan hanya ruang transaksi, tapi juga arena simbolik tempat orang mencari pengakuan, pelampiasan, bahkan pelarian. Rojali dan Rohana datang bukan hanya karena ingin tahu harga barang, tetapi juga ingin merasa menjadi bagian dari dunia konsumsi itu, meski secara aktual tidak mampu berpartisipasi secara ekonomi.
Secara psikologis, perilaku mereka bisa dipahami melalui mekanisme kompensasi simbolik. Ketika seseorang tidak mampu membeli barang mewah, mereka bisa memperoleh semacam kepuasan semu hanya dengan mendekati objek tersebut. Mencoba sepatu mahal, menyentuh bahan baju branded, atau bahkan hanya memandangi tas seharga jutaan rupiah. Semua itu bisa memunculkan sensasi afektif: rasa puas, rasa “nyaris memiliki”, atau bahkan ilusi sementara tentang keberdayaan.
Ini mirip dengan konsep dalam psikologi perilaku yang disebut vicarious consumption, konsumsi secara tidak langsung, dengan membayangkan diri sebagai konsumen, meski tak benar-benar membeli. Dalam dunia digital, bentuknya adalah scrolling marketplace tanpa check-out. Dalam dunia nyata, wujudnya adalah Rojali dan Rohana yang menjadikan mall sebagai wahana “konsumsi pengalaman”.
Fenomena ini juga berkaitan dengan status aspiratif. Banyak orang datang ke mall bukan karena ingin membeli sekarang, tetapi karena ingin “merasakan dulu atmosfer kemewahan” sebagai bentuk afirmasi identitas. Mereka membayangkan, suatu saat akan mampu membeli barang-barang itu. Dengan berada di sana, mereka merasa sedang mendekat pada versi ideal diri mereka. Sebuah identitas yang lebih mapan, lebih sejahtera, lebih bergengsi. Mall menjadi arena proyeksi masa depan, bukan sekadar tempat jual-beli.
Di sisi lain, perilaku ini juga memperlihatkan sisi ironi dari masyarakat konsumen. Kapitalisme ritel menciptakan ruang terbuka yang mengundang semua orang, tetapi secara ekonomi hanya melayani segelintir yang mampu membeli. Rojali dan Rohana menjadi “penonton tetap” dalam pertunjukan kemewahan yang tak mereka sanggupi. Mereka masuk, melihat, bertanya, mencoba, tapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari transaksi. Dalam psikologi ekonomi, ini bisa menimbulkan kecemasan status dan bahkan rasa rendah diri.
Lebih jauh, kehadiran Rojali dan Rohana bisa juga dibaca sebagai bentuk ritual sosial baru. Aktivitas “belanja tapi tidak beli” memberikan struktur waktu bagi banyak orang: pergi ke mall menjadi kegiatan keluarga, ajang pertemuan sosial, atau sekadar hiburan gratis. Mall menawarkan fasilitas yang relatif murah; AC, toilet bersih, ruang bermain anak, bahkan spot swafoto yang instagramable. Maka, fungsi mall bergeser dari pasar ekonomi menjadi ruang publik alternatif.
Secara ekonomi, kehadiran Rojali dan Rohana bisa dianggap tidak menguntungkan. Namun, dari perspektif sosial psikologis, mereka punya kontribusi tak kasat mata. Kehadiran mereka menciptakan keramaian, membentuk atmosfer ramai yang justru menjadi daya tarik mall itu sendiri. Banyak brand tahu bahwa pengunjung yang ramai, meski tidak semua membeli, tetap menjadi strategi visualisasi “tempat ini laku”, yang bisa menarik konsumen sejati. Dalam teori ekonomi perilaku, ini dikenal sebagai efek sosial (social proof); orang terdorong membeli di tempat yang tampak ramai.
Kendati demikian, efek psikologis bagi Rojali dan Rohana sendiri bisa beragam. Beberapa mengalami emosi positif: rasa senang, lega, puas karena bisa “mengakses dunia atas” meski cuma sebentar. Tapi sebagian lain bisa merasa makin frustrasi, terutama jika kunjungan ke mall memperkuat kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Frustrasi ini bisa berkembang menjadi impulsif purchase di kemudian hari. Saat seseorang memaksakan pembelian demi mengobati rasa malu atau ingin “membuktikan diri”.
Fenomena ini juga terkait dengan norma sosial baru yang diproduksi oleh budaya konsumen, yaitu gagasan bahwa belanja adalah bentuk validasi diri. “Kalau kamu tidak belanja, kamu bukan siapa-siapa” adalah pesan tidak langsung dari iklan, display toko, dan feed media sosial. Dalam kerangka itu, Rojali dan Rohana menjadi korban sistemik dari ekonomi visual. Mereka terseret ke arena yang penuh ilusi, tapi tidak punya cukup peluru untuk bermain.
Lalu, apakah perilaku mereka irasional? Tidak juga. Dalam kerangka psikologi ekonomi, manusia tidak selalu bertindak demi untung-rugi finansial. Mereka seringkali bertindak demi kenyamanan emosional, penerimaan sosial, dan harapan akan kemungkinan masa depan yang lebih baik. Jadi, meski secara praktis mereka “mengganggu” staf toko karena tidak membeli, secara psikis mereka sedang melakukan proses pembentukan makna terhadap hidup dan harapan mereka.
Masyarakat, khususnya kelas menengah yang rentan, perlu difasilitasi untuk memahami batas antara konsumsi simbolik dan kesejahteraan nyata. Literasi finansial bukan hanya soal mengatur uang, tapi juga tentang mengelola ekspektasi, keinginan, dan tekanan sosial. Orang harus belajar bahwa tidak memiliki barang mahal bukan berarti gagal. Sebaliknya, hidup sederhana tapi terencana adalah bentuk kemapanan sejati.
Pihak pengelola mall dan brand juga bisa berperan dengan menciptakan ruang inklusif. Mungkin tidak semua orang bisa membeli, tapi mereka bisa merasakan pengalaman yang bermakna. Misalnya, toko-toko bisa menyediakan informasi edukatif, ruang interaksi tanpa tekanan membeli, atau sekadar hospitality yang ramah. Rojali dan Rohana bukan musuh. Mereka adalah bagian dari lanskap sosial yang hidup, yang perlu dipahami alih-alih dicemooh.
Rojali dan Rohana adalah simbol zaman: mereka hadir sebagai refleksi dari harapan, keterbatasan, dan realitas ekonomi kita. Mereka bukan sekadar pengunjung mall yang “cuma numpang nanya”, tapi potret masyarakat yang terus mencari celah untuk ikut merasakan sedikit kemewahan, meski hanya lewat pandangan mata dan lamunan semu. Kita bisa menertawakan mereka, tapi jangan lupa, kita mungkin pernah jadi bagian dari mereka. Barangkali kita masih sering mengulanginya hingga kini, hanya dengan cara yang lebih tersembunyi.