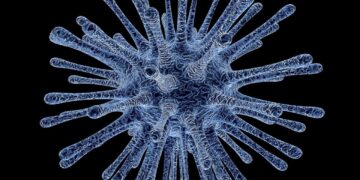Di banyak kampung atau kompleks perumahan, pemilihan ketua RT, RW, atau panitia acara seharusnya menjadi urusan sederhana. Cukup kumpul warga, ajukan nama calon, lalu putuskan lewat musyawarah atau pemungutan suara ringan.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Alih-alih jadi ajang mempererat persaudaraan, momen seperti ini kerap berubah menjadi ajang adu gengsi. Semua karena ego dan masalah pribadi yang ikut dibawa ke ruang publik.
Fenomena ini tampak sepele, tapi dampaknya bisa serius. Ketika ego dipelihara dan masalah personal ditarik-tarik dalam urusan masyarakat, yang rusak bukan hanya hubungan antarindividu, melainkan juga esensi kekeluargaan yang menjadi pondasi kehidupan sosial kita. Ego, pada dasarnya, adalah naluri manusia untuk membela kepentingan diri sendiri.
Namun dalam konteks bermasyarakat, ego yang tak terkendali bisa menjadi racun. Seseorang yang terlalu sibuk memperjuangkan kepentingan pribadinya cenderung sulit menerima kritik, enggan mengalah, dan merasa dirinya selalu paling benar. Akibatnya, urusan yang harusnya rampung lewat obrolan sederhana justru melebar jadi pertikaian.
Masalah pribadi juga sering kali terbawa ke ranah sosial. Misalnya, dua warga yang pernah berselisih soal hutang piutang atau persoalan keluarga, lalu saat pemilihan RW, salah satunya berusaha mati-matian agar lawannya tidak terpilih. Konflik personal seperti ini kemudian menjadi bahan bisik-bisik warga, menimbulkan polarisasi, bahkan merusak kepercayaan sosial.
Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial kerap muncul ketika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Pandangan ini menjelaskan mengapa masyarakat bisa mudah retak hanya karena ego yang dibiarkan menguasai ruang publik.
Ketika ego dan masalah pribadi menunggangi momen politik warga, dampak yang muncul tidak main-main. Kebersamaan terkikis, gotong royong yang dulu jadi ciri khas berubah jadi ajang saling curiga. Polarisasi masyarakat pun terjadi, warga terbelah menjadi kelompok pro dan kontra yang sulit disatukan. Hubungan yang tadinya hangat berubah menjadi persaingan penuh emosi, sementara rasa percaya memudar. Padahal, Koentjaraningrat menegaskan bahwa gotong royong adalah inti kebudayaan Indonesia. Jika nilai ini luntur karena ego, maka harmoni sosial pun akan runtuh.
Di sisi lain, dasar hukum kita sebenarnya sudah mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial. Pancasila sila ke-3 menekankan Persatuan Indonesia, yang berarti kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sila ke-4 mengajarkan bahwa kerakyatan harus dijalankan lewat musyawarah, bukan lewat adu ego.
Bahkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, namun kebebasan itu tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merusak kerukunan.
Kerukunan yang retak sebenarnya bisa diperbaiki jika ada kesediaan untuk menurunkan ego dan kembali pada semangat musyawarah. Masyarakat perlu mengadakan forum terbuka yang jujur dan adil, dengan peran kuat dari tokoh formal seperti ketua RT atau kepala desa, dan tokoh informal seperti tokoh agama atau sesepuh yang dihormati. Aktivitas sosial kolektif seperti kerja bakti, arisan, pengajian, hingga olahraga bersama dapat menjadi sarana merekatkan kembali hubungan yang renggang.
Robert K. Merton dalam teorinya tentang anomi menjelaskan bahwa masyarakat akan rapuh ketika norma bersama tidak lagi dijadikan acuan. Karena itu, budaya saling menghargai, norma gotong royong, serta sikap saling memaafkan harus terus dijaga agar konflik personal tidak merusak keutuhan warga.
Mengembalikan harmoni bukan hanya tugas pemimpin, melainkan tanggung jawab semua unsur masyarakat. Pemimpin formal menyediakan aturan dan forum, tokoh informal memberi teladan moral, pemuda menggerakkan kegiatan sosial, ibu-ibu menjaga kehangatan lewat komunitas, dan setiap individu bertanggung jawab mengendalikan sikapnya.
Kerukunan bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja, ia harus dirawat, dijaga, dan diperbarui setiap saat. Masyarakat yang sehat tidak lahir dari seragamnya pilihan, melainkan dari kesediaan menerima perbedaan dan menurunkan ego demi kepentingan bersama.
Menunggangi momen politik warga dengan ego dan masalah pribadi hanya akan membuat urusan sederhana menjadi rumit. Lebih jauh, hal itu merusak esensi kekeluargaan yang seharusnya menjadi perekat masyarakat. Pertanyaannya sederhana: apa gunanya menang dalam konflik kecil, jika yang hilang adalah kebersamaan yang jauh lebih besar?
Kerukunan adalah pondasi utama masyarakat. Tanpa itu, semua pencapaian tidak berarti. Maka sudah saatnya kita belajar menata ego, memisahkan urusan pribadi dari kepentingan umum, dan kembali pada nilai musyawarah serta gotong royong.
“Kerukunan tidak lahir dari siapa yang paling keras bersuara, tetapi dari siapa yang paling tulus menurunkan egonya demi kebahagiaan bersama.”