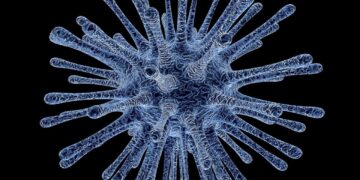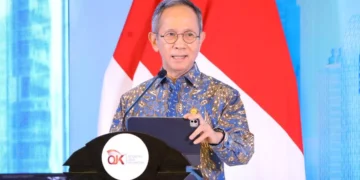Purwakarta tidak lahir begitu saja. Di balik tata ruang yang kini dikenal sebagai kota kecil dengan alun-alun rapi dan jantung pemerintahan di sekitar Jalan Gandanegara, tersimpan lapisan sejarah panjang tentang bagaimana sebuah “dalem” dan tanah shalawat menjadi poros awal berdirinya pusat kekuasaan di wilayah Karawang bagian barat. Kisah ini bermula dari pergeseran fungsi pemerintahan dan tradisi religius yang melebur dalam ruang kota — sebuah proses yang kemudian melahirkan Alun-Alun Kiansantang seperti yang kita kenal sekarang.
Pada masa awal abad ke-19, wilayah yang kini menjadi Purwakarta masih merupakan bagian dari Kabupaten Karawang. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Wanayasa, daerah perbukitan yang sejuk namun cukup jauh dari jalur perdagangan utama. Seiring waktu, lokasi itu dianggap kurang strategis. Pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih datar dan mudah diakses, yang kini dikenal sebagai Purwakarta.
Pemindahan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga simbolik. Di titik pusat kota baru itu dibangunlah “Dalem Shalawat” — rumah besar tempat tinggal sekaligus kantor bagi bupati. Dalam konsep tradisional Jawa-Sunda, “dalem” merupakan pusat spiritual sekaligus politik, tempat di mana seorang pemimpin menjalankan pemerintahan dengan nilai religius. Kata shalawat sendiri memberi makna keberkahan dan doa bagi rakyat yang dipimpinnya. Maka, Dalem Shalawat tidak sekadar gedung, tapi juga penanda bahwa kekuasaan dan keagamaan berpadu di tengah masyarakat Purwakarta kala itu.
Dikutip dari tulisan R.M.A. Ahmad Said Widodo dalam artikel “Sejarah Alun-Alun Kiansantang Purwakarta dan Brigade III Kiansantang di Purwakarta”, gagasan tentang Dalem Shalawat ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan ruang pemerintahan modern di Purwakarta. Dari situlah tata kota dengan pusat alun-alun, masjid agung, dan pendopo bupati mulai terbentuk, mengikuti tradisi arsitektur dan tata ruang kerajaan Jawa yang menempatkan spiritualitas dan pemerintahan dalam satu garis lurus.
Di depan Dalem Shalawat inilah kemudian terbentuk alun-alun — lapangan luas yang menjadi pusat aktivitas sosial dan pemerintahan. Alun-alun bukan hanya ruang publik, melainkan simbol keterbukaan antara penguasa dan rakyat. Di masa kolonial, lapangan ini menjadi tempat apel prajurit, perayaan hari besar, hingga arena pengumuman kebijakan pemerintah. Sementara bagi rakyat, alun-alun adalah ruang interaksi — tempat berdagang, bersosialisasi, hingga menonton pertunjukan rakyat.
Seiring perkembangan zaman, nilai-nilai di sekitar alun-alun itu tetap bertahan, meski fungsinya berubah. Setelah Indonesia merdeka, kawasan ini tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Di sekitar alun-alun dibangun kantor bupati, pendopo, dan masjid agung — mengulang pola klasik tata ruang kerajaan: masjid di barat, pendopo di utara, dan pasar di timur. Susunan ini menunjukkan bahwa nilai spiritual, kekuasaan, dan ekonomi tetap harus berjalan seimbang dalam kehidupan masyarakat.
Nama Kiansantang yang kini melekat pada alun-alun juga bukan sembarang nama. Sebelum menjadi sebutan resmi, nama itu telah hidup dalam budaya lokal sebagai representasi tokoh legendaris — Prabu Kiansantang, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang dikenal karena semangat perjuangan dan perjalanan dakwahnya di tanah Sunda. Mengambil nama itu untuk alun-alun berarti menghadirkan kembali semangat kepahlawanan dan religiusitas ke dalam ruang publik Purwakarta. Dengan kata lain, Alun-Alun Kiansantang bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi juga pengingat akan jati diri masyarakat Sunda yang menjunjung keberanian, kearifan, dan spiritualitas.
Namun, makna nama “Kiansantang” di Purwakarta ternyata lebih dalam lagi. Ia tak hanya merujuk pada tokoh legendaris, tapi juga berkaitan erat dengan satuan militer yang pernah berjaya di wilayah ini: Brigade III Kiansantang — pasukan yang berperan penting dalam mempertahankan Purwakarta di masa revolusi. Jejak brigade ini kelak menjadi bagian dari narasi lanjutan yang menegaskan hubungan antara sejarah militer dan identitas kultural kota.
Kini, Alun-Alun Kiansantang menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini. Setiap jengkal tanahnya menyimpan kisah tentang pemerintahan kolonial, perlawanan rakyat, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Renovasi modern yang dilakukan pemerintah daerah tak menghapus jejak lamanya; justru mempertegas bahwa ruang publik ini selalu hidup — dari pusat kekuasaan bupati zaman dulu, hingga menjadi ruang ekspresi masyarakat hari ini.
Di tengah hiruk pikuk modernisasi, berdirinya tugu, patung, dan bangunan-bangunan baru di sekitar alun-alun seolah menjadi lapisan baru dari sejarah panjang itu. Setiap kali lonceng masjid agung berdentang dan anak-anak bermain di halaman yang dulu tempat apel pasukan, sejarah Dalem Shalawat seakan berbisik: bahwa Purwakarta dibangun di atas doa, kerja keras, dan semangat perjuangan yang diwariskan lintas generasi.