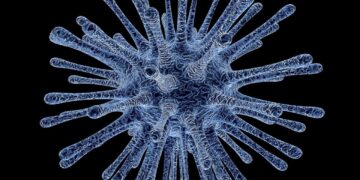Kapan terakhir kali Anda melihat postingan yang isinya murni tentang bersantai? Bukan healing ke Bali, bukan staycation mewah, tapi rebahan murni di kasur sambil bengong dan menatap langit-langit kamar yang kusam?
Jawabannya, pasti jarang. Kalau pun ada, biasanya itu adalah plot twist setelah si empunya akun pamer tumpukan to-do list dan layar laptop dengan wallpaper pemandangan Alaska.
Kita ini hidup di zaman yang aneh, coy. Dulu, orang yang sibuk itu adalah orang yang memang pekerjaannya nggak bisa diganggu, yang mungkin gajinya dua digit, atau minimal punya pabrik kerupuk. Hari ini? Sibuk adalah kewajiban moral.
Kalau Anda nggak sibuk, berarti Anda gagal dalam hidup. Kalau malam Minggu Anda nggak ada janji brunch atau meeting mendadak, Anda wajib merasa bersalah karena telah membiarkan detik-detik berharga terbuang sia-sia.
Media sosial kita sudah jadi semacam etalase ‘kesibukan’ yang absurd. Kita rela merekam layar laptop yang menunjukkan cursor bergerak panik antara dua file Excel, lengkap dengan caption sok filosofis, “When the work-life balance is just a myth.” Padahal, aslinya kita cuma geser-geser kolom dan ngopi tanpa tujuan jelas.
Fenomena “Kerja Jam 2 Malam”
Coba perhatikan, postingan paling populer di Instagram Story atau LinkedIn hari ini adalah potret layar laptop jam 02.17 dini hari. Di sebelahnya, ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin, atau rokok yang tinggal separuh. Latar belakangnya wajib remang-remang, seolah-olah dia sedang menjalankan misi rahasia menyelamatkan dunia, padahal cuma merevisi slide presentasi yang isinya 80% template dari Canva.
Kenapa jam 2 pagi? Karena bekerja jam 10 pagi itu nggak dramatis. Bekerja jam 10 pagi, kita hanya terlihat sebagai karyawan yang taat aturan. Tapi bekerja jam 2 pagi? Itu adalah Status Sosial Tertinggi. Itu berarti Anda adalah seorang hustler, orang yang dikejar deadline gila, atau, yang paling parah, “bos muda yang seleranya kopi manual brew.”
Padahal, 90% dari kita yang pamer sibuk jam segitu sebenarnya adalah korban manajemen waktu yang buruk. Kita sok-sokan fokus dari jam 8 malam, tapi ternyata setengah jam habis buat scroll TikTok, sejam buat debat di Twitter, dan sisanya mikir keras mau ngopi di mana. Alhasil, pekerjaan yang harusnya selesai magrib, molor sampai dini hari.
Dan setelah semua kerepotan itu, apa yang kita dapat? Validasi. Self-praise. Rasa puas karena feed kita terlihat lebih ‘berisi’ daripada tetangga sebelah yang cuma posting kucing.
Antara Healing dan Hustling
Satu sisi, kita didorong untuk hustling sampai lupa napas. Sisi lain, kita diwajibkan untuk healing ke tempat yang Instagramable biar nggak dibilang depresi. Kedua hal ini harus dipamerkan.
Intinya, kita nggak boleh diam. Diam itu membosankan, dan yang paling parah, diam itu nggak menghasilkan konten.
Coba sekali-kali, kita berani jujur. Kita bikin status: “Hari ini saya berhasil menghabiskan waktu 4 jam tanpa melakukan apa-apa selain menatap plafon dan memikirkan hutang.” Atau, “Saya nggak sibuk. Kerjaanku selesai jam 3 sore. Sisanya mau main gim.”
Pasti nggak ada yang mau like, bahkan mungkin ada yang unfollow. Karena di era ini, kejujuran itu nggak menjual, bestie. Yang menjual itu ilusi.
Jadi, mari kita akui saja. Kita semua budak validasi. Dan selama validasi itu bisa didapatkan hanya dengan memotret kabel charger laptop jam 03.00 pagi di balik asap rokok, maka ya sudah. Selamat bekerja keras demi terlihat paling sibuk, ya, coy. Jangan lupa caption-nya harus pakai bahasa Inggris, biar terkesan global.