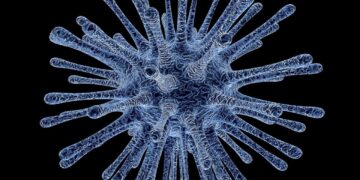Sejak dulu, di negeri yang konon gemah ripah loh jinawi ini, mahasiswa dipandang lebih dari sekadar bocah ingusan yang ke mana-mana bawa totebag isi laptop. Mahasiswa adalah “ras terkuat” di bumi pertiwi. Kontribusi mereka dalam menyuarakan kebenaran bukan kaleng-kaleng; sejarah mencatat dengan tinta emas (dan sedikit darah) bagaimana teriakan mereka pernah menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan yang, katanya, tak tersentuh.
Mari kita putar waktu sebentar. Ingat 1966? Saat harga beras melambung dan politik carut-marut, mahasiswa turun dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Rezim Orde Lama pun goyang.
“Sejak 10 Januari 1966, puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi di jalanan selama lima hari berturut-turut,” kenang Jusuf Wanandi tokoh KAMI dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998, dari sebuah tulisan Martin Sitompul dalam Historia.
Lalu, loncat ke Mei 1998. Gedung kura-kura di Senayan itu tiba-tiba berubah warna jadi lautan almamater. Soeharto, The Smiling General yang berkuasa 32 tahun, akhirnya “lengser keprabon” karena desakan anak-anak muda yang muak dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Aksi-aksi mahasiswa itu telah dimulai sejak permulaan 1998, seperti dikutip dari Krisis Masa Kini dan Orde Baru (2003) oleh Muhammad Hisyam. Salah satunya oleh mahasiswa Universitas Indonesia atau UI pada Januari 1998. Mereka mengeluarkan pernyataan permintaan agar Soeharto mundur secara damai untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru dikutip dari tulisan Hendrik Khoirul Muhid, Tempo.
Mahasiswa bukan lagi sekadar pelajar, mereka adalah martil sejarah yang menghantam tembok tirani.
Romansa Jalanan dan Parlemen Trotoar
Dari sejarah itulah, aksi demonstrasi menjadi “ritual suci”. Turun ke jalan bukan sekadar hobi panas-panasan biar kulit tanning atau ajang cari jodoh lintas fakultas (walau ada juga yang begitu). Demonstrasi adalah mekanisme check and balance paling purba dan paling efektif ketika saluran diplomasi buntu.
Ketika para elit politik sibuk main mata dan birokrat kampus pura-pura budeg, maka jalanan adalah parlemen yang sesungguhnya. Di sana, TOA bukan sekadar pengeras suara, melainkan senjata. Poster-poster nyeleneh bukan sekadar meme, melainkan kritik tajam yang menembus jantung kekuasaan. Peran mahasiswa di sini jelas: menjadi “penjaga” yang memergoki—bahkan menghantam—ketika tuan rumah (baca: pemerintah atau rektorat) mulai maling di rumah sendiri.
Tanpa aksi massa, perubahan sering kali cuma jadi wacana di ruang seminar ber-AC yang dingin dan sepi.
Civitas Academica atau Kuli Berdasi?
Namun, di balik heroisme masa lalu dan gempita aksi jalanan, kita perlu duduk sejenak dan bertanya: Sebenarnya, apa sih kita ini?
Secara definisi mentereng, kita adalah bagian dari Civitas Academica. Komunitas ilmiah yang otonom, independen, dan menjunjung tinggi mimbar akademik. Kampus, idealnya, adalah benteng terakhir akal sehat. Ia bukan pabrik yang didesain sekadar mencetak “tukang” atau “kuli berdasi” yang siap diperbudak industri.
Pendidikan tinggi seharusnya membebaskan manusia, bukan sekadar melatih skill mengetik cepat atau menghafal pasal. Tri Dharma Perguruan Tinggi—Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat—adalah mandat suci. Artinya, urusan mahasiswa bukan cuma IPK 4.0 dan lulus cepat (meski itu penting buat emak di kampung), tapi juga memastikan bahwa ilmu yang didapat tidak menguap di menara gading.
Sialnya, definisi ini sering kali dikaburkan. Kampus perlahan berubah jadi korporasi. Mahasiswa dianggap customer, dosen dianggap buruh pengajar, dan Rektorat bertindak bak CEO yang anti-kritik. Ketika logika dagang masuk kampus, nalar kritis sering kali mati suri.
Maka, mencampuri “dapur rektorat” bukan tindakan kurang ajar. Itu adalah upaya mengembalikan marwah Civitas Academica ke relnya. Kalau kampus mulai sewenang-wenang menaikkan UKT tanpa transparansi, atau membungkam suara kritis dengan ancaman drop out, saatnya mahasiswa berhenti jadi “kupu-kupu” (kuliah-pulang) dan mulai jadi “kura-kura” (kuliah-rapat).
Karena sejatinya, mengganggu kenyamanan birokrat kampus yang korup adalah bagian dari ibadah sosial yang paling hakiki.
Mengintip Resep Dapur Rektorat
Maka, kembali ke pertanyaan awal: urusan apa saja yang fardhu ‘ain (wajib bagi tiap individu) untuk kita campuri? Jawabannya sederhana, yakni segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak di kampus.
Jangan biarkan dapur rektorat tertutup rapat. Mahasiswa berhak tahu bumbu apa yang mereka pakai saat meracik kebijakan. Apakah bumbu “pengabdian” atau micin “proyekan”?
Kalau toilet mampet berbulan-bulan, itu urusanmu. Kalau parkiran semrawut sampai helm hilang, itu urusanmu. Kalau dosen killer mematikan nalar kritis mahasiswa dengan ancaman nilai, itu urusanmu. Kalau ada pelecehan seksual yang ditutup-tutupi demi “nama baik”, itu urusanmu yang paling mendesak!
Jangan mau jadi mahasiswa yang cuma datang, duduk, dengar, diam, dan pulang (5D). Itu gaya Orde Baru. Jadilah mahasiswa yang datang, lihat, kaji, kritisi, dan solusi (5K?).
Mencampuri urusan kampus bukan berarti kurang kerjaan. Justru, itu latihan terbaik sebelum kita benar-benar terjun ke hutan rimba bernama “Masyarakat”. Kalau mengurus transparansi dana himpunan saja kita gemetar, bagaimana mau mengurus anggaran negara?
Jadi, wahai mahasiswa yang budiman, mulailah kepo. Mulailah cerewet. Anggaplah kampus itu rumah sendiri. Kalau atapnya bocor, masa iya kita diam saja menunggu banjir?
Panjang umur perjuangan! (Dan panjang umur juga buat mahasiswa yang berani protes meski tugas kuliah dan ujian semesternya belum kelar).