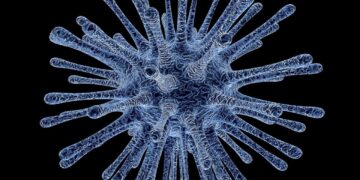Di banyak wilayah, masyarakat sering menghadapi situasi di mana hukum formal belum mengatur secara rinci hal-hal yang mereka jalani sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, musyawarah warga menjadi jalan utama untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, “Apakah keputusan musyawarah berarti membuat aturan baru yang melanggar hukum yang sudah ada?” Jawabannya tidak selalu demikian.
Landasan hukum adalah pijakan aturan resmi yang digunakan untuk memastikan suatu tindakan atau kebijakan dijalankan secara sah. Bentuknya bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau regulasi lain yang mengikat secara legal. Namun, hukum formal umumnya hanya memberi kerangka besar, bukan petunjuk teknis yang sangat mendetail.
Sebagai contoh, dalam pengelolaan kegiatan kampung atau lingkungan, hukum mungkin hanya mengatur bahwa “keputusan boleh diambil secara demokratis oleh warga,” tanpa menyebutkan bagaimana teknis pelaksanaannya.
Di sinilah peran musyawarah menjadi penting. Musyawarah mengisi ruang kosong yang tidak diatur oleh hukum formal. Warga duduk bersama, membahas apa yang paling sesuai, dan menyepakati tata cara atau aturan teknis yang dianggap adil dan relevan.
Contoh sederhana, ketika warga ingin mengatur sistem ronda malam. Tidak ada aturan hukum yang mengatur giliran jaga secara spesifik. Maka warga bermusyawarah dan sepakat untuk menyusun jadwal, menetapkan denda bagi yang absen, dan memberikan pengecualian bagi lansia. Keputusan ini bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan bentuk penguatan nilai kebersamaan yang tetap berada dalam koridor hukum yang lebih besar.
Musyawarah sebagai Pelengkap, Bukan Pengganti Hukum
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara Indonesia, hukum harus adaptif terhadap dinamika masyarakat, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi. Ini berarti hukum tidak boleh kaku. Ketika masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak diatur secara rinci, musyawarah bisa menjadi bentuk adaptasi yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional, seperti keadilan dan kesetaraan.
Musyawarah bukanlah tandingan hukum, melainkan jembatan ketika hukum belum memberikan jawaban spesifik. Syaratnya, hasil musyawarah tidak menyimpang dari hukum yang lebih tinggi.
Dalam teori hukum modern, Hans Kelsen, seorang ahli hukum dari Austria, menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat. Dalam teorinya yang dikenal sebagai Stufenbau, ia menyatakan bahwa setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
Dengan kata lain, hasil musyawarah warga bisa menjadi aturan teknis lokal, tetapi tetap harus tunduk pada aturan resmi seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Jadi, warga boleh membuat kesepakatan asalkan tidak melanggar aturan utama yang berlaku di atasnya.
Agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, hasil musyawarah warga perlu didokumentasikan. Dokumentasi ini bisa dalam bentuk risalah, berita acara, atau keputusan tertulis yang disepakati bersama. Ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban sosial dan administratif.
Hukum dan musyawarah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan mufakat, keduanya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.
Musyawarah bukan pelanggaran hukum, melainkan jembatan antara aturan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan memahami posisi hukum dan fungsi musyawarah, masyarakat bisa lebih percaya diri mengambil keputusan lokal tanpa takut melanggar aturan, asalkan tetap patuh pada nilai-nilai dasar hukum yang lebih tinggi.