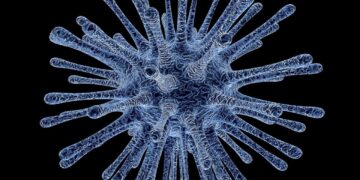Pariwisata sejak lama menjadi salah satu kekuatan pendorong interaksi antarbudaya, pertukaran pengetahuan, sekaligus penggerak roda ekonomi di berbagai belahan dunia. Namun, dalam perkembangannya, pariwisata tidak selalu menghadirkan dampak positif. Fenomena yang kerap disebut sebagai overtourism atau pariwisata berlebihan telah membawa banyak masalah serius, mulai dari kerusakan lingkungan, meningkatnya biaya hidup bagi penduduk lokal, hingga hilangnya nilai keaslian suatu tempat.
Kota-kota seperti Venesia, Barcelona, hingga Bali sering menjadi contoh nyata dari bagaimana gelombang besar wisatawan bisa mengubah wajah suatu destinasi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan kultural. Jika pariwisata awalnya dimaknai sebagai ruang untuk menikmati keindahan dan belajar menghargai keragaman dunia, kini ia sering dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat lokal.
Pertanyaan penting pun muncul: adakah jalan tengah yang mampu membuat pariwisata tetap hidup, namun tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, ekologi, dan kearifan lokal? Dalam konteks ini, pendekatan filosofis bisa menawarkan perspektif yang berbeda. Filsafat mengajarkan kita untuk menimbang bukan hanya apa yang tampak di permukaan, melainkan juga nilai-nilai yang mendasari tindakan manusia.
Filsafat tentang kehadiran, kesadaran, dan rasa hormat dapat memberi arah baru bagi pariwisata yang lebih berwawasan, sehingga perjalanan tidak lagi sekadar konsumsi destinasi, melainkan menjadi pengalaman penuh makna bagi pengunjung dan berkah bagi penduduk lokal. Seorang filsuf kontemporer mungkin akan mengatakan bahwa pariwisata berlebihan terjadi karena manusia sering memandang perjalanan sebagai ajang pemenuhan hasrat konsumtif.
Banyak wisatawan pergi bukan untuk “hadir” secara otentik, melainkan sekadar mengoleksi foto, video, atau tanda bukti digital bahwa mereka pernah berada di suatu tempat. Dalam kerangka pemikiran Martin Heidegger, misalnya, tindakan seperti ini bisa dilihat sebagai bentuk “pelupaan akan keberadaan” karena wisatawan hanya sibuk dengan representasi, bukan dengan pengalaman yang sejati.
Padahal, inti dari perjalanan seharusnya adalah kesadaran akan kehadiran: hadir secara penuh, mendengarkan denyut kehidupan setempat, dan membuka diri terhadap perjumpaan manusiawi. Di sisi lain, filsafat etika, terutama etika Emmanuel Levinas, menekankan pentingnya menghormati l’Autre atau “Yang Lain”.
Dalam konteks pariwisata, ini berarti mengakui bahwa penduduk lokal bukanlah sekadar penyedia layanan atau latar belakang eksotis bagi liburan seseorang. Mereka adalah subjek dengan martabat, tradisi, dan hak untuk hidup dengan nyaman di tanah mereka sendiri. Dengan demikian, pariwisata yang berwawasan harus dibangun atas dasar rasa hormat; bukan hanya hormat terhadap manusia, tetapi juga terhadap lingkungan yang menopang kehidupan bersama.
Jika wisatawan mampu memandang penduduk lokal sebagai “wajah yang harus dihormati”, maka pariwisata tidak lagi sekadar transaksi ekonomi, melainkan sebuah dialog antarmanusia yang saling memperkaya. Kehadiran dan rasa hormat menjadi dua kunci utama yang dapat memandu transformasi pariwisata. Kehadiran mengajarkan wisatawan untuk benar-benar hidup dalam momen ketika mereka mengunjungi sebuah destinasi.
Misalnya, alih-alih berlari dari satu tempat populer ke tempat lain untuk menuntaskan daftar perjalanan, wisatawan bisa meluangkan waktu lebih lama di satu desa kecil, berbincang dengan penduduknya, menikmati makanan sederhana dengan tenang, dan membiarkan dirinya menyerap atmosfer kehidupan sehari-hari. Kehadiran ini menghadirkan kualitas perjalanan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kuantitas destinasi yang berhasil dikunjungi.
Rasa hormat, di sisi lain, mengingatkan wisatawan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan meninggalkan jejak, baik fisik maupun sosial. Hormat berarti tidak merusak situs budaya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak bersikap arogan terhadap adat istiadat, serta tidak menawar harga barang atau jasa dengan cara yang merendahkan martabat penjual.
Hormat juga berarti menyadari bahwa destinasi bukanlah panggung yang diciptakan hanya untuk wisatawan, melainkan ruang hidup nyata bagi orang-orang yang menetap di sana. Dengan rasa hormat, pariwisata bisa berubah dari sekadar eksploitasi menjadi bentuk solidaritas.
Menerapkan filsafat ke dalam praktik pariwisata tentu bukan hal yang mudah. Pariwisata modern sering kali terjebak dalam logika kapitalisme global yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak wisatawan dianggap semakin baik, karena itu berarti lebih banyak pemasukan. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata cenderung mempromosikan destinasi secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sosial.
Di titik inilah dibutuhkan keberanian untuk mengadopsi perspektif filosofis: menimbang kembali makna kesejahteraan, mempertanyakan nilai “lebih banyak” yang selalu diagungkan, dan beralih pada paradigma “lebih bijaksana”. Sebagai contoh, konsep pariwisata berbasis komunitas yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia bisa dipandang sebagai bentuk konkret dari filsafat kehadiran dan rasa hormat. Dalam model ini, wisatawan diajak untuk tinggal bersama penduduk, belajar kearifan lokal, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat.
Alih-alih hanya menjadi penonton, wisatawan hadir sebagai sahabat yang berbagi cerita, tenaga, bahkan pengetahuan. Hubungan yang tercipta bukan lagi hubungan jual beli, melainkan hubungan kemanusiaan yang lebih sejati. Penduduk lokal pun tidak merasa terasing di tanah mereka sendiri, melainkan justru berdaya untuk menampilkan identitas dan nilai-nilai budaya mereka dengan bangga.
Dalam ranah lingkungan, filsafat ekologi yang dikemukakan oleh Arne Naess melalui konsep deep ecology bisa memberikan pijakan moral. Menurutnya, manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Diterapkan dalam pariwisata, ini berarti wisatawan perlu menahan diri dari tindakan yang merusak ekosistem, sekaligus ikut menjaga keberlanjutan destinasi.
Melalui kehadiran dan rasa hormat, wisatawan bisa menghayati bahwa mengunjungi hutan, pantai, atau gunung bukanlah semata-mata “menikmati pemandangan”, tetapi sebuah perjumpaan dengan realitas alam yang memiliki hak untuk lestari.
Jika filsafat mampu menyentuh kesadaran wisatawan, maka pariwisata bisa menjadi ruang kontemplasi dan transformasi diri. Seseorang yang bepergian dengan penuh kehadiran dan rasa hormat akan kembali dengan pengalaman batin yang lebih dalam: ia belajar rendah hati di hadapan keragaman dunia, ia memahami keterbatasan dirinya sebagai bagian kecil dari ekosistem besar, dan ia memperoleh pelajaran moral dari interaksi dengan penduduk lokal.
Perjalanan seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat global, karena melahirkan manusia yang lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih peduli. Di masa depan, ketika jumlah wisatawan global terus meningkat, solusi filsuf ini menjadi semakin relevan. Dunia membutuhkan pariwisata yang tidak lagi digerakkan hanya oleh nafsu konsumsi, tetapi oleh kesadaran etis.
Keberlanjutan pariwisata tidak bisa hanya ditopang oleh kebijakan teknis seperti pembatasan jumlah pengunjung atau tarif masuk destinasi, melainkan juga oleh revolusi kesadaran wisatawan itu sendiri. Tanpa perubahan cara pandang, kebijakan teknis hanya akan bersifat tambal sulam. Tetapi dengan menanamkan kehadiran dan rasa hormat sebagai prinsip, pariwisata bisa bertransformasi menjadi jalan bagi kedamaian, keadilan, dan harmoni.
Filsafat mengingatkan kita bahwa perjalanan bukan hanya soal berpindah tempat, tetapi juga soal bergerak dalam batin. Wisata yang berwawasan mengajak kita untuk bertanya: apa arti hadir di dunia ini, apa arti menghormati sesama manusia, dan apa arti menjaga bumi yang kita tempati bersama.
Jika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kesadaran yang jernih, maka pariwisata tidak lagi menjadi ancaman, melainkan sebuah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik, baik bagi pengunjung maupun bagi penduduk lokal. Inilah inti dari pariwisata yang berwawasan: menghadirkan diri dengan penuh rasa hormat, sehingga setiap perjalanan tidak hanya berharga sebagai kenangan pribadi, tetapi juga sebagai kontribusi bagi kemanusiaan dan keberlanjutan bumi.