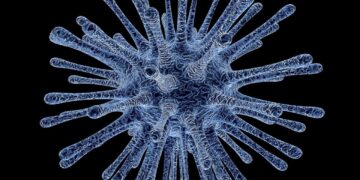Kalau biasanya masyarakat khawatir dengan kabar kenaikan harga BBM, kali ini kabar datang dari arah yang lebih subtil — bukan soal harga naik, tapi angka yang akan dihapus.
Pemerintah sedang bersiap melakukan langkah besar dalam sejarah keuangan Indonesia: redenominasi rupiah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah rampung pada tahun 2027. Rencana ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, yang diteken pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.
Buat orang awam, istilah redenominasi mungkin terdengar seperti nama obat flu atau judul skripsi mahasiswa ekonomi. Tapi intinya sederhana: pemerintah ingin menyederhanakan nominal uang kita, menghapus beberapa nol dari rupiah agar lebih “proporsional”.
Singkatnya, harga nasi goreng yang sekarang Rp15.000 akan jadi Rp15. Kedengarannya murah, kan? Tapi jangan senang dulu — karena sebenarnya sama saja. Nilainya tetap, cuma tulisannya saja yang lebih ramping.
“Contohnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Nilai barang dan jasa tidak berubah, hanya penulisannya saja yang disesuaikan.” ucap Menkeu Purbaya.
Jadi, tidak ada daya beli yang berkurang, tidak ada uang yang lenyap. Negara tidak sedang main sulap.
Redenominasi bukan devaluasi — tapi upaya mempercantik tampilan rupiah agar tidak kelihatan “kelebihan nol” di mata dunia internasional.
Masalahnya, di dunia nyata, psikologi manusia tidak sesederhana tabel konversi. Bagi masyarakat, angka kecil sering diartikan sebagai harga murah. Kita terlalu terbiasa dengan logika visual, bukan logika ekonomi. Jadi ketika melihat “Rp5” di papan harga nasi goreng, otak langsung memicu reaksi: “Murah banget, beli dua!” — padahal dompet tetap sama tipisnya.
Redenominasi Bagi Anak Kost
Bayangkan kehidupan setelah redenominasi diterapkan. Anak kost pergi ke warung, lihat menu bertuliskan “Nasi telur 7 Rupiah”. Ia mengira hidup akhirnya berpihak kepadanya. Ia pesan dua porsi, tambah es teh. Tapi ketika bayar pakai QRIS, ia sadar: tetap empat belas ribu versi lama. Bedanya cuma di jumlah nol yang tidak lagi mengintimidasi.
Fenomena ilusi ini akan merebak. Anak sekolah melihat harga bakso Rp10 dan merasa seperti hidup di era 80-an.
Karyawan melihat slip gaji Rp7.000 (setara tujuh juta lama) dan merasa seperti buruh harian, meski sebenarnya masih sama. Para pedagang warung mungkin jadi target pertanyaan baru: “Bu, ini 5 Rupiah itu yang lama apa yang baru?”
Media sosial pun bisa meledak dengan meme:
“Gaji gue sekarang cuma 5.000, tapi bisa beli motor, thanks redenominasi!”
Lucunya, semua ini hanya terjadi karena mata kita sudah terlalu terlatih menilai angka, bukan nilai.
Namun, efek paling menarik dari redenominasi mungkin bukan pada ekonomi, tapi pada psikologi sosial.
Bagi sebagian orang, melihat angka kecil bisa memberikan rasa “ringan” — seolah hidup lebih terjangkau.
Bagi yang lain, terutama yang bangga dengan nominal besar di rekening, ini bisa terasa menyakitkan. Uang 100 juta yang dulu terlihat prestisius, kini hanya tertulis 100 ribu. Kalau tidak siap mental, bisa-bisa dibilang: “Wah, saldo kamu segitu doang?”
Dari sisi teknis, redenominasi punya banyak manfaat. Transaksi jadi lebih cepat, sistem akuntansi lebih efisien, dan citra rupiah di mata internasional lebih gagah — tidak lagi dipenuhi nol seperti kode rahasia.
Mesin kasir, laporan keuangan, hingga sistem perbankan akan lebih rapi.
Namun, tidak semua efeknya seindah brosur kebijakan. Masa transisi pasti bikin bingung. Akan ada dua versi uang beredar: “rupiah lama” dan “rupiah baru”. Kebingungan ini bisa membuka ruang manipulasi harga.
Misalnya, barang yang semula Rp1,3 dibulatkan jadi Rp2 demi kemudahan. Kecil memang, tapi kalau semua naik setengah rupiah, inflasi bisa datang diam-diam seperti mantan yang tiba-tiba ngechat tengah malam.
Selain itu, efek psikologis “harga murah palsu” bisa membuat konsumsi berlebihan. Orang jadi lebih boros karena merasa semua barang terjangkau. Padahal sebenarnya, daya beli tetap sama — hanya persepsinya yang berubah.
Kalau tidak hati-hati, redenominasi bisa jadi bukan alat efisiensi, tapi jebakan ilusi.
Pada akhirnya, redenominasi adalah upaya negara untuk menata simbol, bukan mengubah realitas. Nol dihapus dari kertas, tapi tidak dari kehidupan sehari-hari.
Harga bakso mungkin terlihat lebih kecil, tapi perut tetap butuh isi yang sama.
Redenominasi mungkin akan membuat catatan akuntansi jadi rapi, tapi tidak menjamin isi dompet jadi tebal.
Karena yang berubah hanyalah tulisan, bukan kemampuan kita untuk menahan diri di depan diskon atau promo tanggal kembar.
Jadi kalau nanti harga mie instan ditulis “3,5 Rupiah”, nikmatilah sensasi murahnya — tapi ingat: uang bulananmu tetap sama, hanya saja kali ini nol-nya sudah ikut berkurang.