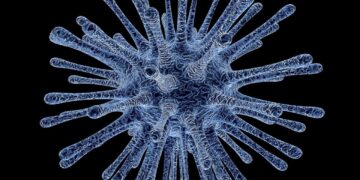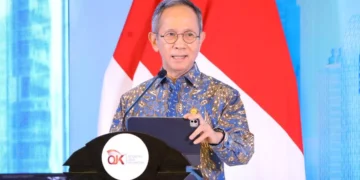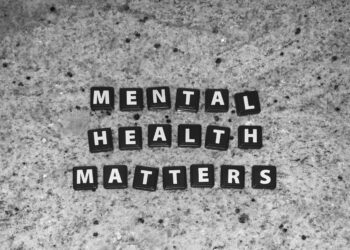Nongkrong sekarang udah kayak kebutuhan primer buat anak muda, nyaris setara sama makan, tidur, dan isi kuota internet. Rasanya ada yang kurang kalau seminggu nggak mampir ke coffee shop estetik, pesan kopi susu gula aren, duduk sambil pasang earphone, lalu foto gelasnya buat di-upload ke Instagram story. Captionnya pasti nggak jauh-jauh dari “healing dulu bestie” atau “me time biar waras.” Padahal kalau dipikir-pikir, healing-nya sering lebih mahal daripada saldo e-wallet kita yang tinggal empat digit.
Dulu, nongkrong di kafe bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Nongkrong di kafe pernah jadi simbol gaya hidup elite, tempat orang-orang kelas atas melepas penat dengan suasana cozy dan aroma espresso yang strong. Kusasi (2010) bilang, pada awalnya budaya kafe hanya dilakukan kelompok masyarakat atas.
Sementara itu, orang-orang dari golongan bawah lebih memilih warung kopi sederhana yang harganya jelas lebih bersahabat. Tapi sekarang? Nongkrong di kafe udah menjelma jadi budaya massa—budaya yang dinikmati semua kalangan tanpa peduli status sosial.
Dari anak SMA yang uang jajannya ngepas sampai pegawai kantoran yang gajinya sudah menipis tanggal tua, semua punya hak yang sama buat antre kopi susu yang kalau dirapel seminggu, harganya bisa jadi uang belanja bulanan ibu kita.
Masalahnya, nongkrong hari ini nggak lagi soal ngobrol ngalor-ngidul sama teman. Banyak yang duduk satu meja tapi sibuk scroll TikTok atau Instagram di HP masing-masing.
Ada juga yang lebih sibuk mikirin angle terbaik untuk memotret latte art dibanding memulai percakapan. Nongkrong sekarang seolah jadi panggung buat nunjukin ke orang lain, “Gue punya circle, bro. Gue nggak kuper.” Ini pas banget sama teori Erving Goffman tentang dramaturgi sosial.
Menurut Goffman, kita semua kayak aktor yang lagi tampil di atas panggung kehidupan, mencoba kelihatan keren di mata “penonton”—alias followers kita. Coffee shop estetik jadi latar, kopi jadi properti, dan story jadi skripnya.
Fenomena nongkrong makin terasa ketika ada yang rela duduk berjam-jam di kafe hanya demi numpang Wi-Fi gratis. Laptop dibuka, padahal yang dibuka cuma YouTube atau Netflix, sesekali tab kerjaan biar terlihat sibuk. Pesan kopi satu, duduk empat jam, colokan pun dipake sampai lupa diri. Nongkrong versi “hemat” ini sering dibungkus dengan dalih produktif, padahal kalau jujur, banyak yang cuma butuh tempat buat kabur dari rumah.
Waktu pandemi kemarin, nongkrong fisik sempat terhenti. Tapi anak-anak nongkrong nggak kehabisan akal. Lahir lah tren kopi susu literan yang bisa dipesan via ojek online.
Minuman ini jadi simbol baru nongkrong hemat di rumah. Tapi kalau jujur-jujuran, kita sering beli bukan karena butuh kafeinnya, tapi supaya botol kopi literan itu bisa difoto di meja kerja, lengkap sama caption aesthetic kayak “remote working vibes.” “Kerja remote sambil nyeruput kopi literan,” katanya. Padahal realitanya, kerjaan lebih banyak ketunda karena sibuk pilih filter Instagram.
Sekarang nongkrong bahkan nggak butuh tempat fisik. Discord, voice call, dan Zoom meeting jadi pengganti kursi kayu di coffee shop. Nongkrong digital ini memang lebih hemat ongkos dan nggak perlu dandan ribet. Tapi tetap aja, tujuannya sering sama: pengen diakui. Nongkrong sudah bergeser jadi simbol gaya hidup, bukan lagi sekadar pertemuan hangat.
Padahal kalau dipikir-pikir, nongkrong sendiri nggak pernah salah. Secangkir kopi di kafe memang bisa jadi oase kecil di tengah hidup yang riweuh. Tapi kalau tujuannya cuma supaya nggak dianggap “nggak gaul” di dunia maya, kayaknya kita perlu nanya ke diri sendiri: nongkrong karena pengen ketemu orang atau karena takut nggak keliatan punya kehidupan sosial?
Kalau jawabannya yang kedua, mungkin yang harus kita datangi bukan barista di coffee shop, tapi diri kita sendiri. Karena secangkir kopi, seberapa mahal pun harganya, nggak akan pernah nyelametin kita dari krisis eksistensial—apalagi kalau saldo e-wallet tinggal Rp7.823.