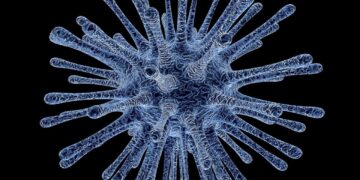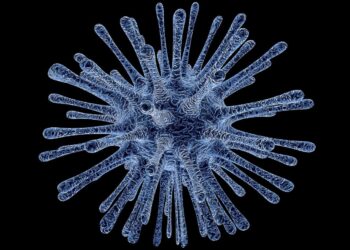Ada banyak hal di Indonesia yang sulit dipercaya, tapi tetap terjadi juga. Salah satunya adalah kenyataan bahwa TPA Cikolotok di Desa Margasari, Pasawahan ini pernah—pernah—diwacanakan menjadi lokasi wisata pendidikan pada tahun 2016. Ya, wisata. Edukasi. Sampah. Tiga kata yang kalau disusun bersama, rasanya seperti punchline stand-up comedy yang tidak sengaja.
Kami datang ke Cikolotok dengan niat mulia: observasi, belajar, dan syukur-syukur pulang masih bisa mencium bau parfume manusia. Tapi begitu mobil melewati radius sekitar 1 kilometer dari titik TPA, kami baru sadar bahwa di sini, bau bukan sekadar masalah—bau adalah atmosfer. Kalau kota lain pakai gapura selamat datang, Cikolotok pakai aroma yang menghampiri sambil menepuk pundak, “Sudah siap? Masuk sini dulu.”
Begitu sampai, kami disambut dua hal: tumpukan sampah setinggi bukit dan barisan lalat yang tampaknya sedang melakukan apel pagi. Lalat-lalat ini betul-betul ramah; mereka tidak menunggu izin untuk ikut rombongan. Mereka langsung menempel, inspeksi, dan mungkin menilai apakah kami layak dijadikan tempat singgah.
Saat kami berbincang dengan warga, aromanya masih saja ikut nimbrung. Bau sampah di sini bukan sekadar polusi, tapi semacam kehadiran spiritual. Sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan meskipun sedang membicarakan topik lain. Bahkan kami sempat merasa, setiap kali warga mulai memaparkan keluh kesah, angin datang membawa aroma lebih kuat, seolah ikut menegaskan: “Nah, ini masalah aslinya!”
Lalu ada hal yang membuat dada mendadak berat: anak-anak. Sebagian terlihat bermain di tonggak-tonggak tanah sekitar TPA, sebagian lain melintas dengan kaki telanjang, dan beberapa tampak memiliki penyakit kulit seperti koreng. Kami tidak berani membayangkan bagaimana keseharian mereka. Sementara kita ribut soal moisturizer dan sunscreen, mereka bergumul dengan lingkungan yang harusnya dikelola negara.
Dan tentang negara—TPA ini kembali mencuat di sekitar pertengahan 2025, ketika DLH disebut-sebut tidak memiliki AMDAL. Lucu juga. Tempat yang sudah menumpuk sampah bertahun-tahun, beroperasi sehari-hari, ternyata bisa hidup tanpa dokumen yang seharusnya menjadi syarat dasar. Mungkin inilah bentuk tercepat dari “efisiensi birokrasi”.
Wacana wisata edukasi itu pun terasa makin absurd setelah melihat kondisi lapangan. Kalau pun jadi, mungkin satu-satunya edukasi yang relevan adalah ini: bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih lebih berbau masalah daripada solusi.
Tetapi di balik satir ini, ada kenyataan yang tidak bisa dibohongi: warga sekitar hidup berdampingan dengan bau yang tidak pernah libur, anak-anak tumbuh dekat gunung sampah, dan para pekerja TPA terus bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Cikolotok bukan hanya tentang sampah yang menumpuk, tapi tentang masalah yang juga ikut menumpuk: tata kelola, kesehatan, prosedur, hingga masa depan. Dan ironinya, gunung sampah ini pernah ingin dijadikan tempat wisata.
Mungkin maksudnya wisata untuk melihat wajah kita sendiri di cermin bernama pengabaian.