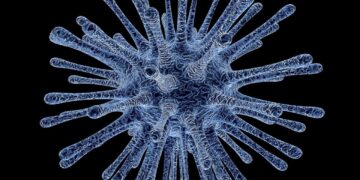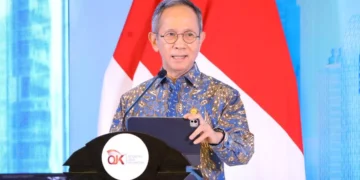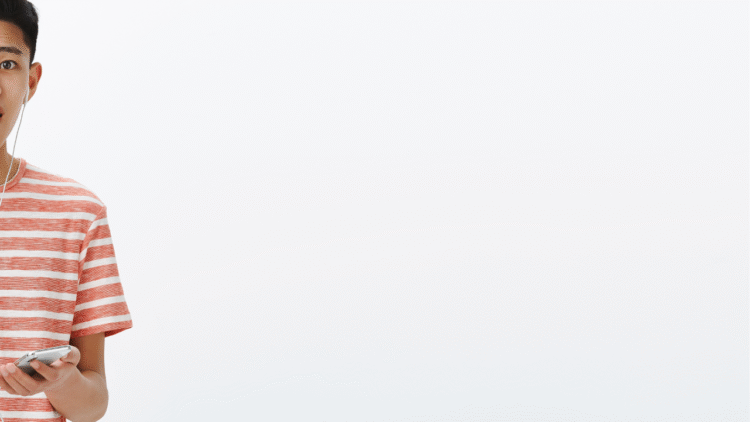Di era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi ajang utama bagi remaja untuk mengekspresikan diri. Fenomena joget dengan gerakan sensual, pakaian minim, hingga gaya bicara yang terkesan “nyeleneh” di TikTok atau Instagram kerap memicu kontroversi.
Bagi sebagian masyarakat, perilaku ini dianggap sebagai tanda kemunduran moral generasi muda—seakan-akan kiamat kecil sudah dekat. Di sisi lain, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk kreativitas dan kebebasan berekspresi yang wajar di era keterbukaan informasi. Supaya kita tidak terjebak dalam pandangan hitam-putih, mari kita pinjam kacamata sosiolog Amerika, Howard S. Becker, untuk memahami fenomena ini.
Howard S. Becker, seorang sosiolog kelahiran 18 April 1928 di Chicago, terkenal dengan karyanya Outsiders (1963) yang memperkenalkan teori pelabelan (labelling theory). Menurut Becker, penyimpangan bukanlah kualitas bawaan pada suatu perilaku atau individu.
Penyimpangan muncul ketika masyarakat memberi label “buruk” pada perilaku tertentu yang menyimpang dari norma dominan. Ia menyatakan, “Penyimpangan bukan kualitas orang jahat, tetapi hasil dari seseorang yang mendefinisikan aktivitas seseorang sebagai buruk.” Dengan kata lain, siapa pun bisa menjadi “penyimpang” jika perilakunya tidak sesuai dengan standar kelompok sosial yang berkuasa.
Kalau kita kaitkan dengan fenomena remaja di media sosial, jelas teori Becker sangat relevan. Joget di TikTok, live streaming sambil makan mic ASMR sampai berbusa, atau flexing uang receh seember sambil bilang “sultan vibes”—semua itu oleh sebagian orang dianggap hiburan receh khas anak muda.
Tapi oleh kelompok lain, terutama masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya, fenomena tersebut bisa dilabeli sebagai “tidak bermoral” atau “penyimpangan.” Di sinilah teori pelabelan bekerja: masyarakat membuat batasan mana yang disebut normal dan mana yang dianggap menyimpang, lalu menempelkan label pada mereka yang menabrak batas itu.
Namun, penting untuk disadari bahwa fenomena ini tidak muncul begitu saja. Budaya digital yang terbuka lebar membawa masuk pengaruh global, mulai dari tren dance challenge ala Barat sampai gaya bicara yang kebarat-baratan. Akhirnya, remaja Indonesia—yang hidup di tengah pluralisme Nusantara dengan norma agama, sosial, dan budaya yang kental—terombang-ambing antara dua arus: mengikuti gaya global yang lebih bebas, atau mematuhi nilai lokal yang lebih ketat. Hal ini menimbulkan benturan nilai yang memicu pro-kontra di masyarakat.
Meski Becker menyarankan kita untuk berhati-hati dalam memberi label, bukan berarti semua perilaku remaja bisa dibiarkan tanpa batas. Indonesia sebagai bangsa dengan keragaman agama dan budaya tentu memiliki nilai-nilai yang dijaga demi harmoni sosial.
Joget sensual di depan kamera mungkin bagi sebagian remaja dianggap biasa saja, tetapi bagi masyarakat Nusantara yang menjunjung kesantunan, perilaku tersebut bisa mengganggu rasa nyaman bersama. Apalagi jika dilihat dari norma agama yang cenderung ketat dalam mengatur ekspresi tubuh dan perilaku di ruang publik.
Selain itu, pelabelan negatif yang terlalu keras justru bisa berdampak sebaliknya. Remaja yang sering disebut “anak nakal” atau “generasi rusak” bisa jadi malah makin menolak norma dominan dan membentuk subkultur sendiri. Fenomena ini sesuai dengan konsep self-fulfilling prophecy dari Becker, di mana seseorang yang diberi label tertentu akhirnya akan berperilaku sesuai dengan label itu.
Di sisi lain, banyak remaja yang membalikkan stigma tersebut. Mereka dengan lantang mengatakan bahwa konten-konten itu adalah hak berekspresi di era demokrasi digital. Dalam pandangan mereka, “masa depan itu milik kami, bukan generasi yang masih pakai ringtone polifonik.” Perspektif ini menunjukkan adanya jurang nilai antara generasi muda dengan generasi sebelumnya yang lebih konservatif.
Melalui perspektif Becker, kita bisa melihat bahwa fenomena joget remaja di media sosial tidak bisa diputuskan hitam-putih sebagai benar atau salah. Penyimpangan yang dituduhkan pada mereka bukanlah sifat bawaan, melainkan hasil konstruksi sosial yang dinamis dan bergantung pada konteks budaya. Namun demikian, penting bagi generasi muda untuk tidak melupakan bahwa mereka hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki aturan dan norma untuk menjaga keseimbangan sosial.
Globalisasi memang membawa banyak tren seru, tapi bukan berarti semua harus ditelan mentah-mentah. Generasi muda perlu belajar memilah mana yang bisa diadaptasi tanpa merusak identitas budaya, dan mana yang sebaiknya disaring demi menjaga harmoni Nusantara. Jangan sampai demi viral beberapa detik, kita kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi perekat bangsa.